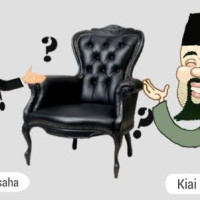Mencari Figur Pemimpin Sumenep 2020

Ilustrasi - Figur Pemimpin (santrinews.com/istimewa)
Siapa yang tepat menjadi figur Bupati Sumenep pada 2020? Menjawab ini tidaklah mudah, apalagi jika dikembalikan kepada masing-masing keinginan individual. Tapi seharusnya perbincangan soal figur harus ditempatkan dalam parameter yang jelas, bukan soal like-dislike.
Apa parameternya? Menjawab ini perlu membedah apa sebenarnya yang menjadi masalah besar di Sumenep. Jika hal ini sudah clear, baru kita beranjak, siapakah figur yang tepat.
Saya mencatat ada beberapa masalah besar yang harus diselesaikan oleh bupati pada masa yang akan datang.
Pertama, soal Sumenep darurat agraria. Ini serius karena menyangkut “tanah air”, tempat segenap aktivitas kemanusiaan berjejak. Jika mau jujur, Sumenep terutama di daerah pesisir telah dikuasai oleh investor untuk kepentingan bisnis individul atau kelompok tertentu.
Jadi masyarakat pribumi telah terkunci pergerakan dan aksesnya ke pantai dan laut. Atau setidak-tidaknya terhambat aksesnya, sehingga apapaun aktivitas ekonomi oleh investor di pantai dan di laut tak bisa diganggu oleh penduduk lokal. Secara geo-politik tentu ini akan sangat merugikan penduduk lokal.
Baca juga: Sumenep Butuh Sosok Pemimpin Seperti Arya Wiraraja
Belum lagi kalau berbicara kekayaan yang akan dikeruk oleh investor atas penguasaan pesisir seperti kekayaan laut, pasir, batu karst, mungkin migas (seperti di saronggi), air, kekayaan alam sebagai tujuan wisata dsb.
Jika di atas lahan itu dibangun industri, apapun jenisnya, maka lambat laun akan mengubah wajah sosial-budaya masyarakat lokal. Jika selama ini tradisi penduduk kental dengan tradisi nahdliyin, ke depan tradisi ini akan mengalami perubahan menjadi tradisi urban atau masyarakat industri yang rasional, formal, kering, dan impersonal. Dalam perubahan seperti ini biasanya mudah disusupi gerakan pemikiran liberal juga fundamentalisme berbasis agama.
Soal ini tak bisa dianggap enteng. Sampai detik ini belum ada upaya pemerintah daerah untuk merespon darurat agraria secara serius dan cerdas. Karena darurat agraria ini sepertinya mendapat legitimasi dan support dari mayoritas birokrasi melalui kebijakan yang memudahkan, termasuk membuka kran selebar-lebarnya investasi. Tanpa pernah menyoal, apakah gelontoran investasi akan memberikan dampak ekologis dalam jangka panjang, merubah wajah sosial-budaya penduduknya, dan juga meminggirkan ekonominya.
Kedua, sejak dulu salah satu masalah besar di Sumenep juga terletak pada birokrasi. Birokrasi di Sumenep benar-benar sosok menakutkan, minta dilayani, dan membangun jejaring yang jauh dari rakyatnya.
Silakan cek kebijakan yang dikeluarkan, pelayanan yang diberikan, karakter birokrasi yang dikembangkan, sistem kinerja yang dibangun umumnya tak mempertimbangkan rakyatnya. Siapapun bupatinya, birokrasi inilah pemenangnya.
Satu sisi, legislatif yang diharapkan memainkan checks dan balances juga gagal. Karena dalam beberapa periode malah gagap dan ikut ritme permainan birokrasi. Sudahlah tak perlu ditutup-tutupi, barter kebijakan (termasuk anggaran) banyak yang tahu.
Istilah “jetimur” (untuk birokrasi/eksekutif) dan “jubara’” (untuk legislatif), bukan sekedar kosa kata politik tak bermakna. Tapi kosa kata ini memendam rahasia tarik-ulur kepentingan antara biroraksi dan legislatif yang akhirnya “happy ending” untuk keduanya. Sementara rakyatnya cukup melongo, karena dalam sejarahnya, rakyat Sumenep sejak jaman kerajaan dikenal sebagai rakyat yang “patuh”.
Ketiga, soal kebijakan bagi kaum dhuafa’ yang tak ada roadmapnya. Terutama soal akses pelayanan. Silakan sisir kebijakan buat buruh tani, buruh nelayan, buruh perusahaan, pedagang kecil, dsb, adakah roadmapnya? Ambil contoh, bagaimana orang-orang kecil ini memperoleh pelayanan kesehatan misalnya?
Keempat, soal nilai-nilai Islam yang mendarah daging dengan budaya lokal di Sumenep, sebagai kabupaten yang dinamika politiknya cukup dinamis tetapi tetap mengedepankan “andhap asor”. Kehidupan seperti ini tidak bisa lepas dari keberadaan pesantren yang perannya sebagai subyek aktif meracik nilai-nilai Islam dan budaya untuk kemudian dihidangkan kepada masyarakat luas, sejak dulu hingga kini.
Menghilangkan peran pesantren berarti gagal memahami alas nilai-nilai dan budaya lokal yang mendasari kehidupan keseharian masyarakat Sumenep seperti sekarang ini.
Dalam soal kebijakan pariwisata, sayang sekali, dirancang secara tergesa-gesa dengan hanya menghitung efek ekonominya, dan itu pun menguntungkan kelompok bisnis tertentu.
Soal efek pariwisata yang makin menjadikan Sumenep “sekuler”, gemerlap tanpa roh, menyeruak ke atas tanpa mengakar ke bawah, mencipta keuntungan ekonomi untuk elit tapi rakyat tetap melarat adalah contoh kegagalan menangkap alas nilai-nilai keislaman dan budaya Sumenep yang sejatinya tegak berdiri di atasnya. Maka tak heran, jika asta (saya tidak begitu suka menyebut “wisata religi) yang sejak dulu menjadi “brand” Sumenep tersisih oleh wisata alam yang dipoles dengan sangat artifisial.
Empat hal ini adalah persoalan besar yang membutuhkan figur yang tahu bagaimana mencari jalan keluarnya dengan cara mendayagunakan kekuatan dan potensi yang ada pada masyarakat Sumenep, tanpa meminggirkan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. (*)
Desember 2019