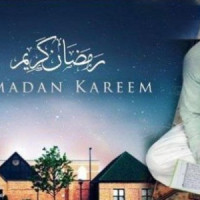Negosiasi Kewajiban Puasa: Dari Boleh Tak Berpuasa hingga Boleh Bercinta Saat Sahur

Puasa disyari’atkan tahun kedua Hijrah, hampir bersamaan dengan kewajiban Jihad, lima tahun setelah kewajiban shalat. Shalat adalah satu satunya kewajiban yang disyari’atkan di periode Makkiyah, yaitu pada tahun ke sepuluh setelah kenabian.
Rasulullah menjalankan puasa Ramadhan sebanyak sembilan kali atau tahun, sebelum beliau kembali ke haribaan sang kekasih, Allah SWT.
Pada mulanya kewajiban puasa Ramadhan bersifat mukhayyar, artinya pilihan, bagi yang mampu berpuasa boleh berpuasa dan boleh tidak puasa tetapi diganti dengan membayar fidyah (memberi makan orang miskin). Sekalipun al-Qur’an menegaskan puasa lebih baik daripada membayar fidyah. (Al-Baqarah, 183-184).
Baca juga: Berpuasa di Tengah Pandemi Corona
Puasa Ramadhan menjadi kewajiban mu’ayyan (bukan pilihan lagi, bukan mukhayyar), ketika ayat 185 al-Baqarah diturunkan. Semenjak ini semua orang yang mampu berpuasa wajib menjalankannya, tidak boleh lagi membayar fidyah. Terkecuali bagi yang sakit dan musafir.
Inilah yang disebut dalam tarikh tasyri’ dengan at-tadarruj fi at-tasyri’ (pembentukan hukum secara evolotif, tahap demi tahap, bukan revolusi, sekaligus). Metode evolutif merupakan salah satu manhaj dakwah al Qur’an.
Selain puasa, pengharaman khamer (yang memabukkan) dalam al-Qur’an juga dilakukan secara evolutif, yaitu melalui empat tahapan sampai masyarakat benar-benar siap, setelah itu barulah khamer diharamkan. Jadi kewajiban puasa berawal dari ringan menuju berat, dari mukhayyar menjadi mu’ayyan.
Namun ada yang menarik, banyak juga hukum Islam yang awalnya berat kemudian menjadi ringan setelah “tawar menawar”, negosiasi antara Rasulullah dan kebutuhan umat. Seperti diketahui, Rasulullah adalah sosok yang sangat demokratis, jika kebijakannya memberatkan umatnya, beliau siap merubah kebijakannya. Jadi kalau Rasulullah tidak pakai gensi-gensian. Pokoknya kebijakannya memberatkan umatnya, beliau siap merubahnya.
Dulu, di awal kewajiban puasa, hubungan suami-istri (jimak) hanya dibolehkan malam hari sebelum tidur. Setelah tidur tidak boleh lagi melakukannya. Jadi dulu, tidak boleh “sahur jimak”, kalau sebelumnya sudah tidur.
Situasi ini, sangat memberatkan para sahabat, sebab banyak yang bekerja sepanjang hari, setelah berbuka sudah tidak kuat lagi menahan tidur, atau anaknya tidak tidur-tidur. Dan baru bangun lagi tengah malam untuk bersahur. Seringkali keinginan jimak tiba-tiba datang di waktu malam ini. Sementara itu, ia dilarang. Maka larangan jimak saat sahur, sangat memberatkan umat. Mengadulah mereka kepada Rasulullah.
Baca juga: Kiai Ali Maksum dan Jomblo yang Tak Tahu Diri
Berdasar pengaduan itu turunlah ayat “…dan di waktu malam dihalalkan bagimu berjimak dengan istrimu, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakain istri.”
Sejak turun ayat ini, suami istri boleh melakukan hubungan sepanjang malam. Pokoknya sebelum kumandang “ash shalatu khairum minan naum”, boleh melakukan “sahur jimak”.
Inilah salah satu karakteristik hukum Islam, pelegislasiannya bersifat evolutif, dan jika kebijakannya memberatkan umatnya, maka Islam siap mengubahnya, tentu tetap dalam batas kebijaksanaan Allah SWT. Wallahu A’lam. (*)
Situbondo, 25 April 2020
KH Imam Nakha’i, Dosen Fikih-Ushul Fikih di Ma’had Aly Salafiyah-Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo.